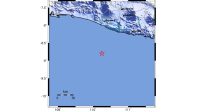Diskusi Bulanan IRE: Problem-Problem Agraria dlm Implementasi UU Desa, di Joglo Winasis, Kamis (28/4/2016). (sutriyati/kabarkota.com)
SLEMAN (kabarkota.com) – Lahirnya Undang-Undang (UU) Desa bisa menjadi berkah ketika Desa mendapatkan gelontoran dana dari pemerintah pusat dan diberi kewenangan sepenuhnya, mulai dari perencanaan hingga pengelolaan dana tersebut. Namun di lain sisi, UU Desa juga bisa menjadi musibah karena ternyata menjadi salah satu pemicu maraknya konflik agraria di berbagai daerah.
Peneliiti IRE Yogyakarta, Dina Mariana mengatakan, berdasarkan hasil riset IRE di empat kabupaten, yakni Kubu Raya, Donggala, Lombok Timur, dan Blitar terjadi banyak kasus konflik agraria karena terkait ketidakjelasan status aset desa setempat.
Pihaknya mencontohkan, Di Blitar, konflik tanah cukup tinggi,karena tanah Negara yang dikelola oleh warga dan telah selesai hak guna usahanya. Sedangkan kasus di Kubu Raya, banyak tanah di sana yang dikuasai oleh Negara ataupun Militer
“Di daerah-daerah luar Jawa, kebanyakan status aset desanya masih tanda tanya,” sebut Dina dalam Diskusi Bulanan IRE: Problem-Problem Agraria dlm Implementasi UU Desa, di Joglo Winasis, Kamis (28/4/2016).
Masih berdasarkan penelitian tersebut, lanjut Dina, ada empat tipologi desa dalam pengelolaan asetnya, yakni cukup banyak aset desa yang hilang, aset tidak fungsional, aset sudah dikelola dengan baik, serta pengelolaan aset yang mampu menambah kuantitas aset
“Konflik agraria terjadi karena terkait inisiatif pengelolaann aset desa sudah jadi, lalu ‘disenggol’ dengan urusan pajak dan status legalitasnya, sebagaimana yang terjadi di desa Bleberan,” sebutnya.
Mantan kepala Desa Bleberan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul, DIY, Tri Harjono juga membenarkan realitas tersebut.
Menurutnya, sekitar 90 persen warga di wilayah tersebut menggarap lahan tanah milik kehutanan, dengan mengajukan permohonan pengeloaan hutan per tahun. “Terbanyak pada tahun 1997-1998,” ungkapnya.
Bahkan, sejumlah titik yang kini menjadi obyek wisata seperti air terjun Sri Getuk dan Goa Pindul juga berada di lahan milik kehutanan.
“Setelah booming sebagai obyek wisata, mulai dipatok (tarifnya) oleh dinas kehutanan,” sesalnya.
Ia menyebutkan, pada awalnya, pihak kehutanan meminta tarif sewa tanahnya Rp 22 juta per tahun dan dikenai kenaikan 10 persen per tahunnya. Namun kesepakatan terakhir, sebesar Rp 13 juta per tahun dan akan naik 10 persen setiap tahun. “Tanah Sultan Ground juga diminta pengelolaannya oleh pihak yang mengatasnamakan keraton,” ujar Tri.
Sementara Dosen STPN, Sutaryono berpendapat, sutaryono problem agraria di desa umumnya terjadi karena ketimpangan struktur pengelolaan tanah. Mengingat, sekitar 40 persen rumah tangga hanya menguasai tanah 0-5 Hektar saja.
“Sekitar 70 persen konflik terkait penguasaan dan kepemilikan aset,” ucapnya.
Selain itu juga menyangkut tapal batas wilayah yang tidak jelas, pengelolaan aset desa yang tidak optimal, serta munculnya oknum-oknum aparat yang ‘main-main’.
Namun begitu, menurutnya masih ada peluang baru untuk melepaskan kawasan hutan yang telah dikelola oleh masyarakat komunal tersebut.
Jika masyarakat komunal yang menguasai hutan itu bisa menunjukkan bukti fisik dari pengelolaannya, lanjut Sutaryono, maka dapat mengajukan permohonan ke kantor pertanahan wilayah untuk dikeluarkan dari kawaaan hutan.
Regulasinya, sebut Sutaryono, berdasarkan pada peraturan bersama empat menteri, Peraturan Menteri ATR/BPN No 9 Tahun 2015, Penetapan Hak Komunal dan Pendaftaran Tanah MHA,IP4t, serta Putusan MK No 35 Tahun 2012. (Rep-03/Ed-03)