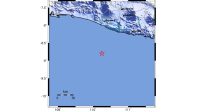SLEMAN (kabarkota.com) – Komunitas Pedulu Kebijakan Kesehatan Indonesia (KPKKI) telah mengirimkan Amicus Curiae (sahabat pengadilan) ke Mahkamah Konstitusi (MK), pada 6 Agustus 2025 lalu.
Amicus curiae berasal dari bahasa latin yang secara harfiah dimaknai sebagai sahabat pengadilan. Ini merupakan praktik dari pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perkara, tetapi memberikan pandangan hukumnya kepada pengadilan karena mereka memiliki kepentingan terhadap perkara tersebut.
Ketua KPKKI, Wahyudi Kumorotomo mengatakan, Amicus Curiae kali ini mereka ajukan untuk memberikan pertimbangan objektif dalam perkara uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta peraturan turunannya.
“Kami melihat bahwa Undang-Undangn Nomor 17 Tahun 2023 yang sebenarnya salah satu UU yang kita harapkan akan memperbaiki layanan kesehatan publik di Indonesia ini ternyata banyak kelemahannya,” jelas Wahyudi di UGM, pada Senin (8/9/2025).
Pihaknya berharap, melalui pengajuan Amicus Curiae ini, UU Kesehatan benar-benar berpihak kepada rakyat.
Wahyudi menyebut, ada sejumlah persoalan penting yang disampaikan ke MK melalui sahabat pengadilan ini.
“Dalam UU ini, kami melihat banyak persoalan, khususnya menyangkut layanan kesehatan yang merupakan hak konstitusional setiap warga negara itu kemungkinan besar akan mengalami pelemahan,” sambungnya.
Itu lantaran kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang seharusnya memberikan hak yang sama kepada setiap warga negara untuk mendapatkan layanan kesehatan yang baik, ternyata sebagian warga justru terpinggirkan dengan aturan yang dibuat.
Pihaknya mencontohkan, Rumah Sakit (RS) yang berada di bawah kendali Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI atau RS vertikal, seluruh kepegawaian hingga pendanaannya diatur oleh kementerian tersebut.
Wahyudi menganggap, dari 37 RS Vertikal di Indonesia, ada kecenderungan bahwa layanan kesehatannya tidak lagi berpihak para kepentingan rakyat karena beberapa alasan.
Pertama, berdasarkan penafsiran UU Kesehatan, Kemenkes membebankan kepada para dokter di RS untuk mengejar target yang bukan cakupan pelayanan, melainkan banyaknya pendapatan yang diperoleh RS karena pemakaian alat-alat dan obat-obatan yang dikeluarkan, meskipun tidak semuanya dibutuhkan oleh pasien.
“Akibatnya, rumah sakit menjadi tempat untuk hal-hal yang sifatnya komersial,” sebut Guru Besar pada Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, Fisipol UGM ini.
Kedua, independensi organisasi profesi dan kolegium. Sebelum UU No 17/2023, kolegium diserahkan sepenuhnya kepada institusi pendidikan dan orang-orang yang memang ahli. Di antaranya, para guru besar di Fakultas Kedokteran, peneliti, dokter spesialis maupun non spesialis yang mengetahui secara persis bidangnya. “Itu adalah lembaga yang benar-benar independen,” tegasnya.
Tetapi dengan UU Kesehatan sekarang, sesal Wahyudi, sebagian besar kolegium ditarik kewenangannya ke Kemenkes. Akibatnya, Kemenkes mengendalikan berbagai macam rotasi dari setiap dokter spesialis di seluruh Indonesia. Jika ada dokter yang menghadapi persoalan, seperti tidak bisa menghasilkan uang maupun pelanggaran, maka Kemenkes berhak sepenuhnya untuk melakukan rotasi atau pun pemindahan mereka ke tempat lain.
Pihaknya berpandangan bahwa jika hal tersebut bertujuan untuk menjaga profesionalisme dokter yang bersangkutan tidak menjadi masalah. Mengingat, akhir-akhir ini ada juga dokter yang melakukan pelanggaran. Hanya saja, jika ini menjadi satu-satunya lembaga yang menghakimi atau menentukan rotasi mereka, maka itu menjadi persoalan serius, karena tidak akan lepas dari faktor like or dislike.
Ketiga, penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di 37 RS vertikal, dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan dokter di Indonesia. PPDS yang diselenggarakan oleh Kemenkes RI adalah PPDS yang berbasis di RS (Hospital Based). Yakni semacam training bagi dokter residen untuk mengamati dan latihan sehingga para akademisi di Fakultas Kedokteran tidak lagi banyak dilibatkan.
Dalam pandangan Wahyudi, keterlibatan RS memang diperlukan dalam hal ini, namun ketika proses pendidikan para dokter spesialis tidak benar-benar mengutamakan keahlian atau profesionalisme, maka dalam praktiknya akan cenderung menghadapi banyak persoalan.
Keempat, mengacu pada UU No. 17/2023 dan Peraturan Pemerintah (PP) 28/2024, Kemenkes melakukan task shifting atau pergeseran tugas. Dokter umum yang sebelumnya tidak melakukan praktik bedah terhadap pasien, tetapi melalui aturan tersebut, para dokter umum di daerah terpencil diperbolehkan melakukan tindakan operasi sesar, dengan alasan kekurangan dokter obstetri dan ginekologi (obsgyn). Padahal selama ini banyak dokter obsgyn yang belum terbebani dengan tugas-tugas itu.
“Hal yang terpenting lainnya adalah bagaimana resikonya?” Sebab, Wahyudi menjelaskan bahwa membedah ibu hamil saat melahirkan itu diperlukan pengetahuan yang sistemik yan hanya dimiliki oleh dokter obsgyn. Ini penting, lantaran sangat berkaitan dengan keselamatan ibu dan anak.
Kelima, persoalan sertifikasi dokter. Selama ini, kolegium melalui Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Surat Tanda Register (STR) dokter, dan bisa melakukan evaluasi ulang atas kompetensi dokter yang bersangkutan.
Sementara dalam UU Kesehatan sekarang STR justru akan diberlakukan seumur hidup tanpa evaluasi sehingga itu akan beresiko. Meskipun alasannya untuk efisiensi biaya sertifikasi yang dianggap terlalu mahal, dan dugaan adanya mafia dalam proses sertifikasinya.
Keenam, melalui PP No. 28/2024, pemerintah mengundang dokter asing ke Indonesia dengan alasan untuk mengatasi masalah kekurangan dokter di dalam negeri. “Tapi perlu diingat bahwa mereka yang datang ke Indonesia itu pasti mengharapkan bayaran yang lebih tinggi daripada dokter di tanah air”.
Wahyudi menilai, langkah itu menambah bentuk komersialisasi di bidang layanan kesehatan, yang justru melanggar hak konstitusi dan menurunkan kualitas pelayanan kesehatan yang semestinya merata untuk seluruh rakyat Indonesia.
Sementara itu, Ketua Pusat Studi Antikorupsi (Pukat) UGM, Totok Dwi Diantoro mengaku tertarik dengan gagasan pengajuan Amicus Curiae karena problem terkait tata kelola dan abuse of power.
Tata kelola dalam konteks ini, sebut Totok, berkaitan dengan pelayanan kesehatan publik yang notabene ada sentralisasi otoritas kekuasaan yang eksesif di tangan Menteri Kesehatan (Menkes). Ini terlihat dari aktualisasinya dalam merumuskan berbagai ketentuan pada UU Kesehatan.
“Prinsipnya, ini mengerucut pada gejala atau gelagat mengenai komersialisasi atau pun industrialisasi di bidang kesehatan. Apalagi ini menyangkut tentang peelayanan kesehatan masyarakat,” tuturnya.
Oleh karenanya, hal ini penting menjadi perhatian bersama. Termasuk, Pukat UGM yang turut terlibat dalam pengajuan sahabat pengadilan kali ini.
Amicus Curiae ini, papar Totok, merupakan wujud proses keterlibatan publik untuk turut serta dalam proses judicial review (uji materi) di MK. (Rep-01)